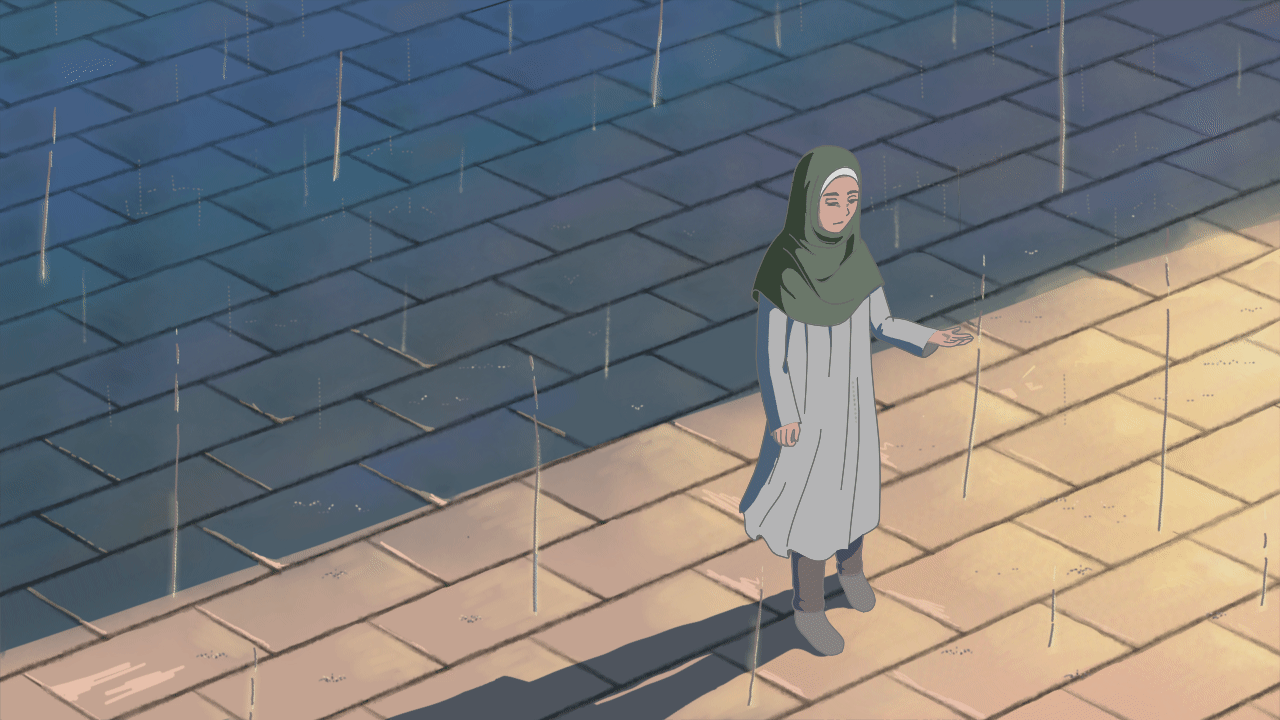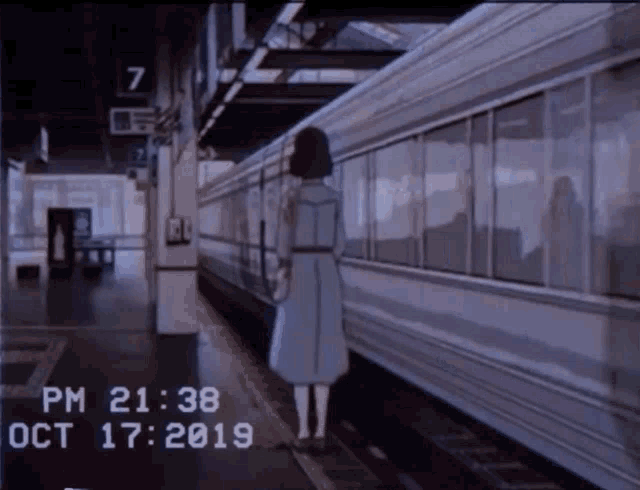Tiba masanya periode sebelum hujan berdamai dengan getirnya tidak diinginkan. Bumi seakan tabah menyaksikan langkah tergesa-gesa sebelum
hujan. Udara bersikap tenang saja mendengar keluh kesah yang berlalu lalang.
Langit bersabar disesaki gumpalan pesan di pikiran manusia menjelang rinai.
Kata-kata menggantung di awan hanyalah payung, secangkir teh, rumah, dan tentu
saja rindu. Sementara dalam diriku bukan kaki, melainkan batin, yang
tergesa-gesa. Di langit bergelayut pesan pencarian yang hampir putus asa.
Orang-orang hanya peduli pada hujan dan rumah--menyudutkan sebelum hujan pada sepi yang kumengerti. Aku, seperti sebelum hujan, mengenali betul rasanya tidak diinginkan. Jiwa ini, sama seperti sebelum hujan, memahami riuh yang mengabaikan kami. Maka kami duduk bersisihan menikmati hening yang dikurung agar tidak gaduh mengaduh.
Meski demikian, sebelum hujan dan aku tak
yakin apakah kami baik-baik saja dipeluk sunyi.
Pada aroma hujan yang bersiap mendekap bumi aku bertanya, seperti inikah perasaan rindu1? Aku telah melewati puluhan ribu hari sibuk mempertanyakan datangnya perjumpaan yang memporandakan raga dalam duga. Jika belum akan dipertemukan, mengapa aku harus memikul perasaan semacam itu? Jika takdir persuaan masih jauh dari harap, tidak bolehkah nanti saja kutanggung beban rasa sebesar ini?
Maka sebelum hujan aku berdoa agar seseorang melintas begitu saja. Saat hujan nanti, aku ingin mengenali wajah yang bersembunyi atas nama rindu. Namun, sejauh mana pun aku bertanya, dia tak kunjung menjelma di hadapku. Hujan telah mempertemukan bumi dan langit sore ini. Sejauh apa dia saat ini untuk bertemu denganku? Apakah ia tidak berdiri di bawah hujan yang sama denganku?
Kenyataan bahwa aku tidak mengetahui apa-apa tentang perkara ini sungguh mengoyak batin.
Aku pulang bersama senyap yang telah nyenyak tertidur di tas punggung. Lengang adalah satu-satunya yang tersisa membersamaiku. Jika aku berkawan baik dengan sunyi, lalu berapa lama lagi topeng bahagia ini bisa kuperankan dengan baik?
Sejujurnya, telah sejak lama aku tak ingin menyeberangi hujan seorang
diri.
----------------------------------------------
1 Terinspirasi dari puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono bahwa hujan begitu tabah merahasiakan rindunya kepada bumi.
"Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan juni
dirahasiakan rintik rindunya kepada pohon berbunga itu"
---------
image source: Muhammad Rifki Adiyanto via Pexels